Dalam Perpres No. 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham) 2021-2025, perempuan masih menjadi salah satu kelompok rentan yang harus diperhatikan. Selain perempuan, dalam Ranham tersebut, kelompok rentan juga dialamatkan pada penyandang disabilitas, anak, dan masyarakat adat.
Ranham ini menjadi angin segar, sebab, dokumen ini menjadi landasan pacu setiap kementerian dan lembaga untuk mengembangkan program dan kebijakan yang memiliki persinggungan dengan beberapa kelompok tersebut. Selain itu, Sustainable Development Goals (SDGs) 2015-2030 menempatkan aspek kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sebagai salah satu program dari 17 program yang menjadi acuan dunia.
Dengan dua dokumen di atas, sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak melihat perempuan sebagai agen pembangunan dan pilar penting perubahan sosial dalam masyarakat. Namun, kesadaran (awarnesse) tentang agensi dan kapasitas bertindak perempuan sebagai paradigma kebijakan (public policy) dan keadilan sosial yang masih rendah menjadi tantangan tersendiri. Oleh sebab itu, perempuan masih dianggap sebagai yang liyan.
Baca juga: Mengandaikan Uma Rimpu, Museum Budaya ala Perempuan Bima dan Indonesia
Sialnya, karena paradigma demikian, suara-suara perempuan menjadi terbatas dan jarang diperhatikan. Padahal, dalam banyak kesempatan, perempuan mampu membuktikan bahwa kapasitasnya setara dan mampu dalam urusan publik dan mendistribusikan keadilan dalam lingkup keluarga, desa, maupun negara.
Etnografi Perempuan
Dalam beberapa kesempatan, saya bertemu dengan beberapa ibu-ibu yang memiliki concern pada pembangunan desa. Umumnya, mereka tergabung dalam beberapa perkumpulan yang berbasis di desanya, seperti majelis taklim, PKK, remaja masjid, posyandu, yang semuanya berbasis pada gerakan perempuan. Mujurnya, dalam kesempatan yang lain juga, saya menyaksikan geliat perempuan dalam kepemimpinan desa. Ada yang menjadi Ketua RW bahkan jauh-jauh hari, dalam ceritanya, ia ingin mengajukan diri sebagai calon ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Dua posisi yang selama ini diidentikkan dengan laki-laki itu.
Agensi seperti ini, tentu saja sangat bagus. Walau masih sebatas niat, keberanian untuk mengungkapkan nawaitu sangatlah penting, apalagi di depan laki-laki dan di depan istri seorang pejabat desa yang jelas-jelas jabatan suaminya akan terancam dengan nawaitu itu. Namun, ia tetap saja bercerita, mengungkapkan keinginannya. Saya apresiatif dengan memperhatikan ceritanya.
Sederet program dan solusinya ia urai. Sederet masalah desanya juga di depan matanya ia tak bergeming. Melanjutkan ceritanya. Apakah Anda juga ingin mendengar ceritanya? Setelah pesan-pesan berikut ini.
Ia buka dengan masalah pengangguran yang menjadi biang masalah sosial di desanya. Katanya, pengangguran ini, salah satu penyebabnya ialah pembangunan. Saya berpikir sejenak. Jelasnya, sebelum masuknya proyek pembangunan di desanya, lahan-lahan produktif digarap oleh pemilik tanah yang kebanyakan berasal dari desanya. Setelah sebuah proyek pembangunan kantor sebuah lembaga masuk, wal hasil, lahan-lahan produktif tersebut ditanami beton, besi, dan aspal mulus untuk kelancaran mobil-mobil mewah pejabat keluar masuk kantor itu.
Sebagian pemilik tanah akhirnya menggarap lahan orang lain, sebagian yang lain menganggur. Tidak ada pekerjaan. Menurutnya, inilah sebabnya, banyak pengangguran di desanya. Efek dari pengangguran ini, kata dia, menyasar pada problem social lain: narkoba, kenakalan remaja, judi online dan offline, dan maraknya rentenir yang menggoda dengan bunga murah, mudah, dan (mungkin) terpercaya.
Selain itu, yang menjadi catatan penting ialah desa, tempat ibu itu tinggal, berada pada posisi strategis. Desanya dilintasi jalan negara, lalu lintas perdagangan antar provinsi bertumpu pada jalan yang membelah desa ini. Lalu-lintasnya sibuk. Sesibuk, ia menggerakkan tangannya ketika berbicara.
Saya yang hanya diam, berpikir, seorang ibu sedang menyadarkan saya tentang “teori pembangunan” dalam ilmu sosial. Teori yang menjadi “buah bibir” mahasiswa era Orde Baru itu. Teori yang (mungkin) bisa menyadarkan orang bahwa pembangunan juga punya andil besar dalam ketidakadilan sosial bagi perempuan. Ya, dalam teori pembangunan atawa modernisasi (dependensi) selalu saja ada pihak yang dirugikan atau tertinggal dalam proses pembangunan. Di satu pihak pembangunan dan modernisasi terjadi, di pihak lain (bisa masyarakat atau yang lain) keterbelakangan sering terjadi.
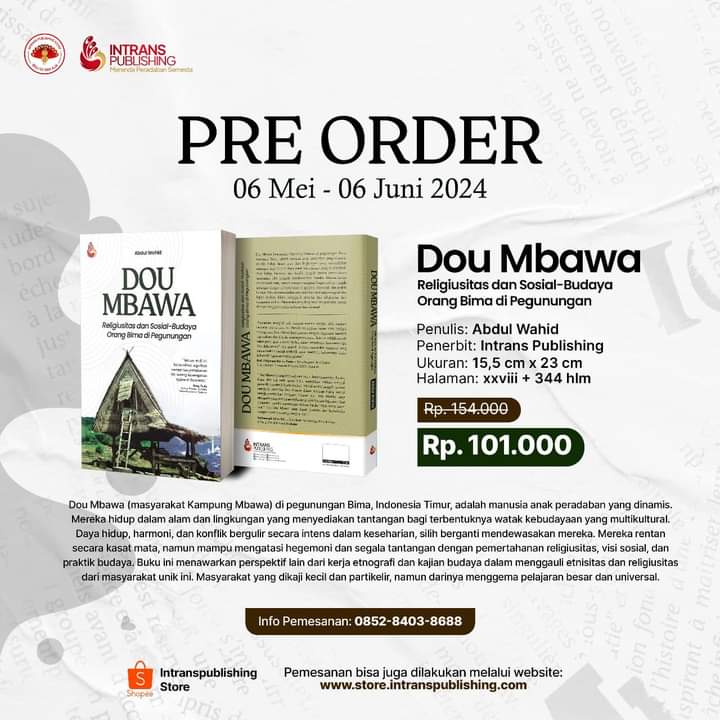
Bingung? Saya jelaskan kembali. Misalnya, di satu daerah ingin membangun sebuah ritel modern, namanya Alfalah Mart dan Indonmaret, yang barang-barang dalam ritel tersebut beraneka ragam dan harganya bervariasi, ya khas modern, apa pun tersedia (ini yang disebut pembangunan atau modernisasi). Untuk pembangunannya, ritel tersebut menggunakan lahan pertanian yang tentu saja dibayar ke pemilik lahan. Setelah itu, masyarakat kebanyakan membeli di ritel tersebut, termasuk si pemilik lahan tadi.
Demokrasi selalu memberi peluang itu. Merawat harapan untuk keadilan sosial dan kesetaraan. Sampai-sampai, Emha Ainun Nadjib menyebut “Demokrasi La Roiba Fih”, tidak ada keraguan di dalamnya.
Masyarakat yang sebelumnya membeli di kios-kios kecil terdekat, akhirnya ditarik ke pusat-pusat ritel itu. Pertanyaannya sekarang, masyarakat yang tidak mampu datang membeli atau menikmati fasilitas ritel itu ke mana? Ya, tetap di kios-kios kecil itu. Namun, karena perkembangan yang masif dan intens, masyarakat juga menginginkan untuk berbelanja di ritel modern itu. Terus uangnya di mana? Nah, Anda bayangkan sendiri, kalau penjabat, ya, korupsi, kalau masyarakat, ya, mencuri. Di sinilah problem sosial yang disebutkan di atas tadi muncul. Nah, masyarakat demikian tentu perkembangannya terhambat (blocked development). (Lihat, Vedi R. Hadiz: 1999).
Dalam situasi demikian, yang berbicara hanya kapital. Siapa yang punya alat produksi dan uang yang bertahan. Di sinilah ibu itu juga menyadarkan saya soal analisis kelas yang kata orang sekolahan itu: Marxian.
Bagaimana solusinya?
Ibu itu, melanjutkan ceritanya. Saya ingin membangun koperasi atau baitul mal yang khusus ibu-ibu, katanya. Pokoknya, agar pengangguran di desanya itu sedikit berkurang. Sebelum ia membangun, kapasitas dan keterampilan dari anggota koperasinya harus dilatih terlebih dahulu. Harus profesional dan manajemennya harus akuntabel.
Baca juga: Dari Aborsi sampai Childfree: Melihat Kerja Metode Mubadalah ala Faqihuddin Abdul Qadir
Ia meyakinkan saya, potensi desa kami sangat banyak. Hasil alamnya melimpah. Tinggal dikelola saja dengan baik. Dengan mengatasi pengangguran ini, maka masalah sosial lain akan mudah ditangani. Perempuan juga harus mandiri dan keluarga di desa ini juga harus menikmati keadilan ekonomi. Desa ini berada di jalur strategis, tapi masyarakatnya tragis, katanya. Ia mengharap dukungan.
Demokrasi dan Keadilan Gender
Seberapa besar kita berharap pada demokrasi? Mungkin besar, termasuk saya. Demokrasi awalnya bisa menjadi peluang bagi pendistribusian keadilan yang merata, termasuk untuk perempuan. Demokrasi selalu memberi peluang itu. Merawat harapan untuk keadilan sosial dan kesetaraan. Sampai-sampai, Emha Ainun Nadjib menyebut “Demokrasi La Roiba Fih”, tidak ada keraguan di dalamnya.
Suara perempuan akan semakin terdengar, seandainya akses dan keadilan dalam konteks elektoral hari-hari ini bersih dari politik uang. Betapa banyak, perempuan yang akan maju dalam tingkat terkecil untuk menyuarakan pemikirannya. Dan itu, mungkin hanya bisa dilakukan dalam alam demokrasi yang sehat. Kesehatan demokrasi menjamin keadilan gender.
Namun, akhir-akhir ini cerita demokrasi Indonesia makin suram. Sesampai di akhir cerita ibu itu. Ia berkata, niat saya besar, tapi apalah daya, ma’alum calon zaman ake, sadia uluku piti walisi, ede waliku masusa masyarakat reni (zaman sekarang, kalau berniat nyalon harus sediakan uang terlebih dahulu). Saya mengangguk.
Ia bangun dari duduknya, lari, mengejar penjual bakso. Ia mentraktir saya, satu mangkuk. Harga lima belas ribu.[]
Ilustrasi: Kalikuma Studio
*Ang Rijal Anas, pemuda, tinggal di Kota Bima

