MUNGKIN ini, “Sisi Lain” yang lain sama sekali. Tentang mereka, orang-orang biasa yang kerja dan nyatanya bisa. Tangan mereka bertuah, dipadu pengalaman, dan dipandu rasionalitas. Tenaga kuda, fisiknya dilatih dengan batu-batu, ototnya terbentuk oleh kayu dan besi. Kulit legam, terbakar matahari. Hitam, petanda mengakrabi situasi. Tubuh dipenuhi keringat “kerja-kerja-kerja”, sebelum kata itu dijadikan jargon politik oleh Si Empunya republik.
Hari ke hari, sampai pekerjaannya selesai. Berharap upah untuk orang rumah. “Demi kau dan si buah hati” mungkin begitu slogan mereka. Waktu petang, pulang. Besok, datang lagi, sampai benar-benar selesai pekerjaan maha mulia itu. Untuk orang lain, generasi lain, mungkin juga untuk anak-anak mereka. Cahaya di ujung terowongan selalu ada. Sambil merawat harapan untuk perubahan dan nasib baik di hari depan. “Siapa tahu?”, kata yang selalu tertanam di pundaknya di atas cadas tua yang mereka angkat.
Ya, ini tentang mereka. Kita menyebutnya tukang batu. Mungkin kalau Anda ke kota-kota besar, mereka akan disebut pekerja, buruh, karyawan, insinyur, atau apa pun hasil kekuatan politik bahasa dan eufimisme penguasa mencengkeram mindset kita. Membentuk dan (seringnya) dibentuk untuk sebuah agenda dan hal-hal lain yang bersifat hegemonik.
Mereka sedang membangun sebuah fasilitas baru pada perpustakaan di tengah kota. Sebelum perpustakaannya terbangun, mereka juga telah memasukkan tangan dan keringatnya untuk perpustakaan itu. Buah tangan mereka membuat pengunjung nyaman dan betah berlama-lama. Menghabiskan waktu dengan buku-buku dan segala fasilitas yang tersedia. Tapi, apakah kita pernah berpikir, mereka juga pembangun peradaban! Tangan mereka membangun kota, keringat mereka jadi pilar-pilar ilmu pengetahuan.
Baca juga: Perempuan, Desa, dan Modernisasi
Mungkin saya terlalu berlebihan, tapi saya punya argumentasinya. Siapa hari ini yang mengetahui siapa yang membangun Candi Borobudur? Gedung-gedung mewah di tengah kota? Atau membangun rumah yang Anda tempati? Untuk pertanyaan pertama mungkin kita akan menyebut nama raja-raja Jawa kuno yang mempekerjakan jin dan makhluk halus. Rasionalisasinya, raja itu hanya menyuruh, loh. Bukan dia langsung mengangkat batu dari bawah ke atas. Dan dalam konteks dulu, mungkin juga tidak digaji. Apabila jin dan makhluk halus, apa iya arsitektur itu tidak dirancang oleh manusia rasional. Pertanyaan kedua dan tiga, Anda jawab sendiri dengan logika yang sama.
Untuk mengungkap itu, manusia membuat ilmu yang disebut sejarah dan arkeologi. Ternyata, untuk membuatnya jelas satu ilmu ditambah lagi, namanya arsitektur. Tidak cukup lagi, sedikit ditambah cultural studies untuk membuatnya teranalisis dengan baik. Ya, tentu, khas ilmuwan, harus dengan metodologi riset dan epistemologi yang ketat, itu. Padahal jika diperhatikan, semuanya itu hanya untuk mengungkap tangan-tangan kecil orang-orang biasa yang membangun itu, juga kebiasaan, dan keganjilan mereka.
Di sela-sela lelah, mereka bercerita tentang apa saja. Kemarin tentang kuda, tentang kuda-kuda politisi lokal dan orang-orang kaya menjadi jawara dan yang tersisih. Kuda-kuda baru yang selama ini menjadi underdog tak lupa mereka sebut. Sampai nama-nama pemiliknya dan dinamika keluarganya seperti apa. Menjadi buah bibir.
Kemudian, manusia modern (generasi selanjutnya) dan orang-orang pintar memperdebatkan hasil karya mereka. Ada yang bilang begini, ada yang mengatakannya begitu. Ada yang “menurut saya”, ada juga yang “mengutip pendapat”, dan seterusnya. Dialektikanya hidup, namun, nama mereka yang berkeringat itu tak pernah disebut ketika hasil karyanya selesai dan berguna. Nama mereka selalu dijadikan anak tiri dalam pembangunan dan jarang dicatat dalam sejarah. Mungkin, sebelum mereka bekerja harus di-SK-kan dulu, agar sejarah mengingatnya dalam dokumennya.
Benar, Pramoedya Ananta Toer, adil memang harus sejak dalam pikiran.
***
Kembali ke mereka yang bekerja untuk membangun fasilitas di sebuah perpustakaan tadi. Seperti yang saya jelasan sebelumnya. Mereka tekun dan telaten dalam menyusun batu-batu membuat dasar sebuah tembok. Batu-batu besar disusun dengan kehati-hatian, di atasnya batu seukuran tangan terkepal untuk menguatkan fondasi bawah. Di sela-selanya dimasukkan semen sebagai perekat dan penguat.
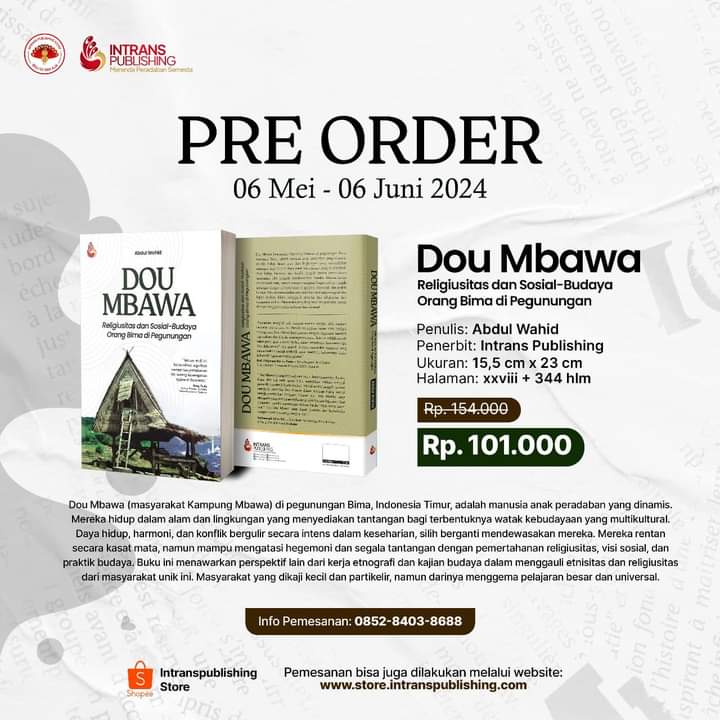
Di sela-sela lelah, mereka bercerita tentang apa saja. Kemarin tentang kuda, tentang kuda-kuda politisi lokal dan orang-orang kaya menjadi jawara dan yang tersisih. Kuda-kuda baru yang selama ini menjadi underdog tak lupa mereka sebut. Sampai nama-nama pemiliknya dan dinamika keluarganya seperti apa. Menjadi buah bibir. Hari ini tentang ciri khas tukang batu di setiap desa. Katanya, di Desa A, biasanya hasil pekerjaannya rapi. Di Desa B, kurang rapi, tapi teknik mereka menyusun batu untuk dasar bangunan bagus. Kalau Desa C, tidak ada sama sekali. Biasanya mereka orang baru, belum ada pengalaman.
Mungkin juga itu menjadi hiburan buat mereka, di bawah matahari yang kian membakar. Di sisi lain, mereka menyalakan speaker, menyetel lagu-lagu “pop cengeng” – meminjam istilah Mahfud Ikhwan – dari Pance Pondaag, Dian Piesesha, dan Nike Ardila. Sesekali terdengar lagu-lagu dangdut. Mungkin ini modus mereka merayakan kekalahan. Merayakan suara orang kecil. Menyadarkan, bahwa kalah-menang hanya soal waktu, tapi merayakannya, itu wajib.
Di mulutnya, selalu ada rokok kretek. Kali ini, mungkin sebagai modus agar mereka terus berkonsentrasi. Asap putihnya, seputih tali yang mereka gunakan untuk menentukan preposisi batu-batu yang mereka susun. Keseimbangan dan presisi batu-batu mereka pakai kayu jati, membentuk persegi. Jelas, pembaca, ini rasional dan ilmu pengalaman. Mereka ukur dengan angka-angka. Besar-kecil, tinggi-rendah, dan panjang-pendeknya. Mereka cerdas, saya bodoh untuk hal yang itu.
Heterarki, sebagaimana yang diungkap oleh Abdul Wahid dan Atun Wardatun (2022) untuk melihatnya dari beragam perspektif dan multi arah menjadi mungkin. Namun, perlu akomodatif agar suara mereka terdengar. Agar pekerjaan maha mulia membangun peradaban itu bukan hanya hegemoni orang pintar secara akademik, orang kaya secara materi, raja-raja dengan kedudukannya, tapi juga mereka yang bekerja di bawah sengatan matahari. Mereka bekerja untuk membangun perpustakaan, tempat orang belajar. Dan itu besar, bukan?
Mereka nyata, bukan seperti mitos Sisyphus, yang mendorong batu itu ke atas gunung dan terjungkal. Mereka juga sedang berusaha, suara dan perannya penting dalam kerja-kerja peradaban yang baik dan terhormat ini.[]
Ilustrasi: Kalikuma Studio
*Ang Rijal Anas, pemuda, tinggal di Kota Bima

